Oleh: Muhammad Ridwan
Membaca Arah Perubahan Sosial dan Budaya
Kebudayaan, menurut Abdul Halim Sani, lahir dari proses dialektika antara langkah berpikir manusia dengan lingkungannya. Sani menegaskan bahwa budaya merupakan perangkat bagi manusia dalam menyikapi realitas lingkungannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ada dua aspek utama dalam pembentukan budaya. Pertama, kerangka berpikir manusia yangg menentukan gimana mereka memahami dan merespons realitas. Kedua, lingkungan yangg memberikan kondisi objektif bagi budaya untuk berkembang.
Dalam konteks pembentukan langkah berpikir, Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa pola pikir perseorangan terbentuk melalui hubungan sosial. Jika dikaitkan dengan budaya, hubungan ini menjadi komponen kunci dalam menentukan corak suatu kebudayaan. Cara berpikir yangg dominan dalam suatu masyarakat bakal mempengaruhi gimana budaya itu berkembang dan bertahan. Lingkungan yangg beragam alias terbatas bakal membentuk karakter budaya yangg berbeda di tiap wilayah.
Lantas, gimana dengan pola pikir masyarakat Indonesia? Tan Malaka beranggapan bahwa masyarakat Indonesia condong menggunakan logika mistika, ialah kombinasi antara pemikiran logis dan mistisisme. Mistisisme dalam konteks ini merujuk pada kecenderungan menjadikan roh, kekuatan gaib, alias entitas supranatural sebagai jawaban atas beragam fenomena.
Salah satu penyebab bertahannya logika mistika dalam masyarakat Indonesia adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan ilmiah. Feodalisme dan kolonialisme menciptakan stratifikasi sosial yangg membatasi akses pendidikan bagi sebagian besar masyarakat. Ketimpangan ini menghalang penyebaran pemikiran logis dan kritis, sehingga logika mistika terus memperkuat sebagai langkah berpikir yangg lebih mudah diterima.
Selain itu, peran pemuka kepercayaan dan budaya juga menjadi aspek krusial dalam membentuk pola pikir masyarakat. Pendekatan yangg mereka gunakan sering kali berbasis doktrin mistisisme, yangg menganggap mereka mempunyai karunia ilahiah. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas spiritual dan menjadikan pandangan mistik sebagai rujukan dalam menghadapi beragam persoalan hidup.
Lingkungan dan Dinamika Budaya
Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam membentuk budaya masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, lingkungan dan alam sekitar menjadi sangat krusial dalam menentukan pola pikir dan kepercayaan. Fenomena alam yangg ekstrem dan keterbatasan teknologi di masa lampau berkontribusi terhadap berkembangnya logika mistika. Sebelum sains berkembang, masyarakat condong menjelaskan kejadian alam melalui dalil-dalil mistisime.
Contohnya, ombak galak di Pantai Selatan dikaitkan dengan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kehendak dari penguasa laut, sementara letusan Gunung Merapi dianggap sebagai bagian dari rencana Eyang Sapu Jagad. Sementara itu, di beragam wilayah Indonesia, seperti Maluku, masyarakat meyakini adanya makhluk gaib di Palung Banda, dan di Kalimantan, masyarakat Dayak percaya pada roh penjaga rimba yangg kudu dihormati agar lingkungan tetap lestari.
Budaya yangg lahir dari perpaduan logika mistika dan lingkungan yangg ekstrem condong berkarakter sakral, penuh dengan ritual, serta menjunjung tinggi otoritas budaya dan pemuka spiritual sebagai penentu kebijakan sosial. Kehidupan masyarakatnya sering kali melangkah dalam harmoni dengan alam, lantaran kepercayaan terhadap roh penjaga alias kekuatan gaib yangg diyakini mengatur keseimbangan lingkungan.
Baca Juga: Abdul Mu’ti Raih Penghargaan The Visionary and Emerging Leadership di Elshinta Award
Namun, di sisi lain, budaya semacam ini juga berisiko menjadi kurang adaptif terhadap perkembangan pengetahuan pengetahuan dan penemuan modern. Pola pikir yangg lebih mengutamakan doktrin misterius daripada pendekatan logis dapat menghalang kemajuan dalam bagian teknologi dan ekonomi. Oleh lantaran itu, diperlukan formulasi yangg memungkinkan pelestarian nilai-nilai tradisional tetap berjalan, tetapi tidak menghalang keterbukaan terhadap perubahan zaman.
Menuju Industrialisasi Kebudayaan
Jika budaya yangg lahir dari logika mistika dan lingkungan condong berkarakter sakral dan ritualistik, maka industrialisasi kebudayaan menjadi krusial untuk memastikan bahwa budaya tersebut tidak hanya lestari, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi yangg dapat mendukung kesejahteraan para pelaku budayanya. Industrialisasi kebudayaan adalah pendekatan yangg mengelola unsur budaya agar dapat dikembangkan secara komersial tanpa kehilangan prinsip nilai-nilai tradisionalnya.
Salah satu pendekatan yangg dapat dilakukan adalah dengan mengemas unsur budaya dalam corak yangg lebih adaptif terhadap permintaan pasar. Ritual adat, mitologi, alias seni tradisional tidak hanya dipertahankan dalam corak aslinya yangg eksklusif untuk kalangan terbatas, tetapi juga dikembangkan menjadi produk imajinatif yangg dapat diakses oleh audien yangg lebih luas.
Misalnya, seni perwayangan yangg menampilkan alur cerita wayang klasik dengan bahasa lokal yangg hanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat original daerah, dapat diubah dengan bahasa Indonesia bakal tetapi tetap ditambahi dengan celetukan bahasa daerah. Hal ini memungkinkan budaya tetap hidup, tidak hanya sebagai warisan yangg dilestarikan, tetapi juga sebagai aset ekonomi yangg menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal.
Selain itu, industrialisasi kebudayaan juga dapat diterapkan melalui sektor ekowisata berbasis budaya, di mana mitos dan kepercayaan tradisional dimanfaatkan untuk menarik visitor tanpa menghilangkan unsur edukasi dan konservasi lingkungan.
Misalnya, organisasi di sekitar Gunung Merapi yang tetap mempercayai mitos tentang Eyang Sapu Jagad dapat mengembangkan paket wisata yangg tetap berpijak pada kearifan lokal, sekaligus membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Model ini juga dapat diterapkan di wilayah lain, seperti pengembangan wisata budaya di area budaya Baduy, Toraja, alias Bali, yangg tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya sembari menghadirkan daya tarik bagi wisatawan.
Namun, industrialisasi kebudayaan tidak bisa melangkah begitu saja tanpa memperhatikan keseimbangan antara nilai ekonomi dan substansi budaya itu sendiri. Jika budaya hanya dikejar dalam konteks ekonomi tanpa memperhatikan autentisitasnya, maka ada akibat komersialisasi berlebihan yang justru mereduksi nilai budaya itu sendiri, dan dapat menyebabkan produk budaya tersebut bakal kehilangan daya tawar.
Oleh lantaran itu, strategi industrialisasi budaya kudu melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari pelaku budaya, akademisi, pemerintah, hingga pihak swasta. Tujuannya adalah agar proses ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memastikan bahwa budaya yangg dikembangkan tetap mempunyai makna dan tidak kehilangan jati dirinya.
Pada akhirnya, perpaduan antara tradisi dan modernitas bakal menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya di era industri kreatif. Dengan pendekatan yangg tepat, warisan budaya yangg telah memperkuat selama beratus-ratus tahun dapat tetap lestari, sekaligus menjadi bagian dari kemajuan ekonomi yangg membawa faedah bagi seluruh masyarakat.
*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta



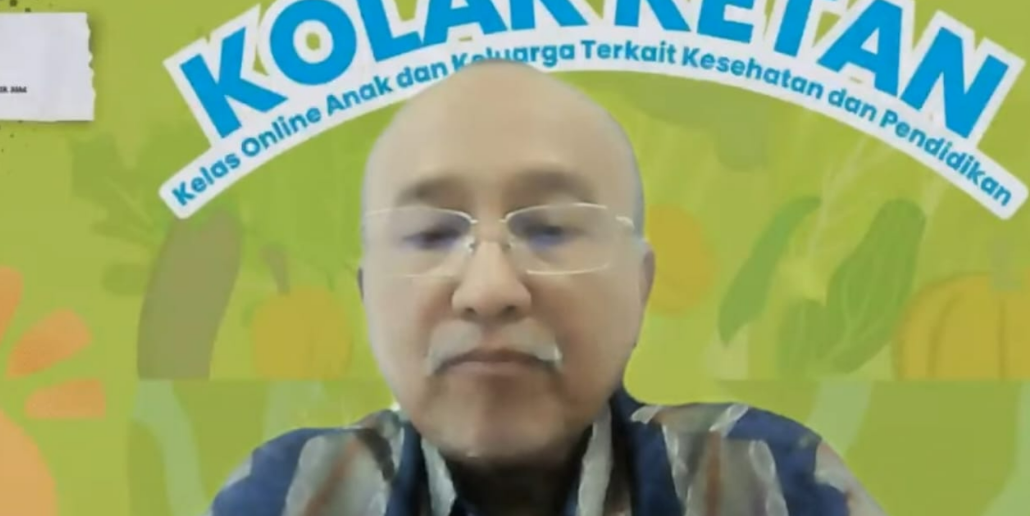








 English (US) ·
English (US) ·  Indonesian (ID) ·
Indonesian (ID) ·